Oleh : Ahmad Arief Tarigan*
PUBLIK kembali 'terperangah' menyaksikan adegan kekerasan yang terjadi. Penggunaan kata ' terperangah' tak lebih dari alasan estetis penambah efek dramatis penceritaan. Mengapa? Tak lain tak bukan untuk bersikap kompromi dengan kebiasaan kultural kita (?), berlagak kritis atas peristiwa yang ada.
Sikap permukaan yang menonjolkan hal ideal, walau pada praktiknya: 'jauh panggang dari api'. Bukankah kita akrab dengan sikap yang demikian? Bukan begitu, begitu bukan?
Demonstrasi mahasiswa yang berujung bentrok dengan pihak keamanan dan belakangan bentrok dengan (yang diberitakan) masyarakat sekitar kampus. Tawuran sesama mahasiswa yang dipicu persoalan sepele. Sebuah peristiwa berulang yang semestinya menjadi bahan refleksi bagi dunia kampus itu sendiri. Tak cukup disederhanakan sekedar gairah 'anakmuda'. Respon minimalis untuk standar akademisi.
Berbagai pemberitaan tentang peristiwa di atas, sejenak menyita perhatian kita. Pikiran dan emosi kita tertumpah deras pada kasus-kasus itu. Segala verbalisme (bernada ironi, sarkasme, sampai empatif) mengalir dari mulut kita. Namun, perlahan tapi pasti, semuanya mereda lantas menghilang ditelan bumi. Sampai kasus berikutnya muncul, kita pun kembali berlatah-ria. Betapa sirkuit memori otak kita seirama dengan nada populisme selayaknya jamur musim 'penghujan' atau tren mode rambut terbaru. Bagi saya, gejala ini mengindikasikan dua hal, pertama, akrabnya kita dengan kultur kekerasan, dan, kedua, rendahnya kesadaran dan upaya strategis jangka panjang membangun kampus.
Ironi
Sudah jadi anggapan umum kalau institusi pendidikan formal, khususnya perguruan tinggi, ialah arena penggodokan intelektual, moral, dan etika. Kampus diharap menghasilkan manusia paripurna. Habitat tempat gagasan dan ide dapat berkembang karena benih-benih penemuan baru direspon secara aktif dan positif. Dialog yang cerdas, sehat, dialektis dan berwawasan adalah 'bahasa' yang disepakati bersama. Argumentasi, hipotesa, sampai perbedaan opini dianggap wajar. Dunia kampus itu dunia kebaruan dan penciptaan. Dunia dimana insan akademik berlomba membuktikan 'kebenaran' dengan penalaran dan kekaryaan. Saling bantah-berbantah lewat karya akademik beserta kebermanfaatannya pada masyarakat. Tri Darma perguruan tinggi.
Penggambaran ideal di atas serasa ironi bila dihadapkan pada realitas lapangan. Peristiwa kekerasan yang melibatkan unsur kampus terjadi berulangkali di berbagai kota. Perulangan peristiwa yang bukan saja mengindikasikan akrabnya kita pada kultur kekerasan, tapi juga, minimnya perhatian pada upaya pencegahan. Fenomena ini pun mengisyaratkan adanya kebuntuan komunikasi wajar dan sehat antar sesama civitas akademik. Ada jurang tak nampak yang menciptakan kebuntuan komunikasi. Secara alamiah, kebuntuan membatu akan mencari pelepasan, maka tinggal menunggu waktu dan pemicu yang tepat: 'bum!', terekspresikan melalui bermacam bentuk kekerasan.
Pendekatan Kultural
Tapi kurang adil apabila menumpukan semuanya ada hanya kepada institusi kampus saja. Padahal banyak faktor yang mendukung kultur kekerasan itu. Minimnya ruang publik yang representatif bagi warga tak pelak berkontribusi pada gejala depresi sosial.
Perkembangan teknologi informasi juga berperan besar menyokong wabah autisme, sebuah keadaan dimana individu begitu kecanduan dengan mesin hape, gadget, smartphone plus aplikasi media sosialnya. Kualitas kecakapan sosial masyarakat menurun. Kepedulian, empati, dan interaksi sosial secara langsung (face to face) mengalami kemerosotan kualitas. Sementara serbuan aplikasi media sosial di jejaring internet kian massif.
Akibatnya kekerasan (fisik) cenderung dipilih sebagai bahasa pengungkapan untuk merespon persoalan sosial yang ada.
Para pembuat kebijakan kampus mesti memperhatikan faktor ini karena pasar terbesar teknologi informasi adalah kaum muda. Mahasiswa bagian dari kaum muda itu sekaligus salah satu unsur pembentuk masyarakat.
Pendekatan pengelolaan gaya lama tentu saja tidak cukup mengimbangi kaum muda 'nirkabel' ini. Sebagaimana karakteristik teknologi infomasi yang diakrabi, mereka ini juga dapat bergonta-ganti 'warna'dengan cepat. Kecenderungan labil yang sering disalahkaprahkan sebagai sebuah kompleksitas’ dan kemajuan 'zaman'. Sebuah generasi penggemar jalan 'pintas' dan lompat 'pagar'
Untuk mengimbanginya, pihak penyelenggara kampus bisa melakukan pendekatan kultural. 'Mengimbangi' adalah pilihan bijaksana untuk menyikapinya. Orientasinya adalah membangun keseimbangan. Bersikap eksklusif, intimidatif, dan menyalahkan tentu saja sebuah gaya lama yang tidak cocok lagi dengan kondisi kekinian. Di samping mengubah kultur birokrasi yang lebih mengayomi, menyediakan ruang-ruang alternatif untuk mahasiswa adalah satu solusi terbaik di antara kebanyakan. Namun, yang paling penting adalah bagaimana civitas akademik bisa menghidupi dan merawat atmosfer akademik di kampus. Membiasakan berdiskusi, menulis, dan mengemukakan pendapat. Sikap terbuka, ilmiah, kritis, dialogis, humanis, dan produktif adalah prasyarat bagi atmosfer itu. Atmosfer akademik adalah proses nyata kampus. Proses yang menentukan seperti apa nantinya produk yang dihasilkan. Maka dari itu, tak salah apabila atmosfer akademik dianggap sebagai benteng pertahanan kampus.[***]
*Penulis adalah pendiri dan aktif di Klub Kajian Budaya


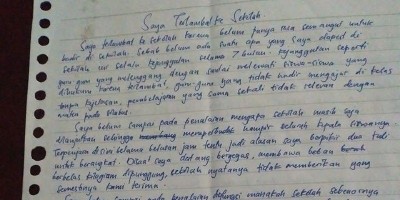












KOMENTAR ANDA