 MUSIM penerimaan mahasiswa baru tiba. Bagi mahasiswa senior, masa ini adalah masa-masa yang dinantikan. Pasalnya masa ini tidak sekadar menjadi ajang tebar pesona pada mahasiswa-mahasiswi baru, tetapi juga sebagai tempat unjuk kebolehan dan unjuk kekuasaan di kampus.
MUSIM penerimaan mahasiswa baru tiba. Bagi mahasiswa senior, masa ini adalah masa-masa yang dinantikan. Pasalnya masa ini tidak sekadar menjadi ajang tebar pesona pada mahasiswa-mahasiswi baru, tetapi juga sebagai tempat unjuk kebolehan dan unjuk kekuasaan di kampus. Siapa pun, yang pernah menjadi mahasiswa pernah menjalani masa ini, entah itu Mapram, Ospek, P3T atau apalah namanya, namun tetap pada satu substansi: pengenalan mahasiswa baru terhadap lingkungan kampus.
Layaknya sebuah pisau, ospek kerap dinilai sebagai sebuah proses turn in di lingkungan kampus yang memiliki dua sisi. Banyaknya ekses negatif membuat banyak juga pihak yang menginginkan kegiatan ini dihapus
Bagi mahasiswa baru masa-masa ini adalah masa yang paling memberatkan. Pelonco dari senior terhadap junior terkadang dirasakan sangat keterlaluan. Mulai dari syarat-syarat tak lazim dalam masa tersebut, hingga hardikan dan perlakuan yang dinilai kejam didapatkan. Sehingga tak jarang dampak psikologis langsung dirasakan dari acara yang bertujuan membangun kekompakan ini.
Salah satu tujuan dari orientasi studi dan pengenalan kampus (ospek) adalah untuk mengenal program studinya. Masalahnya adalah kerap ditemukan ‘kekerasan’ dengan embel-embel pengenalan fakultas atau jurusan.
Tak jarang unsur-unsur ‘ngerjain’ lebih dominan ditemukan dari segala macam konsep yang katanya ada itu. Misalnya, mahasiswa baru disuruh makan mi dingin dengan mata tertutup setelah mencari cacing tanah. Ada juga mahasiswa baru yang disuruh berulang kali mengukur jalan sepanjang puluhan meter dengan jengkal tangan hanya karena senior menyatakan hasil pengukurannya belum tepat. Dan sebagainya.
Peristiwa dan segala bentuk ‘kejahilan’ senior itu mungkin akan selalu manis dikenang, namun tidak ingin diulang oleh setiap mahasiswa. Akhirnya, setelah mahasiswa yang pernah mendapatkan ‘pelajaran’ dalam ospek, kecendrungannya adalah memberikan pelajaran itu kembali pada mahasiswa baru di tahun-tahun selanjutnya.
Dalam sebuah wawancara almarhum psikolog Univiersitas Indonesia, Sartono Mukadis berpendapat, ospek adalah cermin sakitnya masyarakat yang kebutuhannya akan kekuasaan sangat besar.
Kekuasaan itu seberapa pun kecilnya digunakan untuk memanipulasi orang lain, sebagaimana yang terjadi dalam ospek yang dilakukan mahasiswa saat ini. Mahasiswa menjadi bagian dari sistem yang kini memupuk sikap mental yang memanfaatkan kekuasaan untuk korup.
Menurut eks-mahasiswa UI tersebut, mahasiswa kini yang diharapkan muncul sebagai pendobrak tradisi buruk memang berubah. Namun, perubahan yang terjadi pada generasi muda dinilai mengalami paradoks. Ia memberi contoh bagaimana anak baru gede (ABG) sudah berani pacaran kelewatan batas, namun pada saat yang sama masih bergantung sepenuhnya kepada orangtua secara ekonomi.
Sartono menilai, idealnya tradisi ospek yang baru seharusnya diarahkan pada pembentukan mental high achiever.
“Sikap mental di mana orang sudah jatuh, ingin bangkit lagi atau memperbaiki diri, seperti orang Jepang yang walau sudah buat kereta cepat, maunya bikin yang lebih cepat lagi,” katanya.
Namun apa yang terjadi hari ini di ranah kaum intelektualis, ospek hanyalah menjadi kegiatan bodoh, kampungan dan norak. Simbol-simbol militeristik dilanggengkan. Baris-berbaris, penyiksaan fisik, dan pembodohan atas perintah yang sungguh mencerminkan perbuatan kaum feodalitik jaman penjajah. Dengan begitu, omong kosong menanamkan kedisiplinan kepada mahasiswa baru. Sebab apa yang tengah dipertontonkan selama kegiatan ospek berlangsung sma sekali tidak menggambarkan kedisiplinan.
Ketika Perintah Datang
Tidak membayangkan ketika perintah dari senior datang dan mewajibkan mahasiswa junior membawa macam-macam sebagai syarat mengikuti ospek. Sering persyaratan itu tidak masuk akal bagi si mahasiswa baru. Begitu pula dengan orang tua mereka di rumah. Evolusi ospek yang memang telah menunjukkan gradasi penurunan tindak kekerasan tetap saja membuat orang tua di rumah selalu cemas setiap kali mengingat nasib anaknya pada hari-hari pertama menghirup udara perguruan tingkat tinggi.
Tercatat eskalasi kekerasan yang dipraktekkan siswa senior pada junior belakangan ini banyak mengambil korban. Kasus di Institut Teknologi Malang yang merenggut nyawa seorang mahasiswa yang baru-baru ini terjadi menggambarkan dengan jelas bagaimana senior telah menjadi malaikat baru yang sangat menentukan nasib juniornya pada masa orientasi.
Dalam kuliah umum mahasiswa baru di kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya (awal September 2003), almarhum Nurcholis Madjid memaparkan, tradisi perpeloncoan bermula dari Universitas Cambridge, Inggris. Mahasiswa di kampus ini mayoritas berasal dari anak bangsawan Inggris yang borjuis-borjuis. Karena berasal dari strata sosial yang tinggi dan terhormat, mereka terkenal liar, nakal, dan tidak mengindahkan segala bentuk peraturan.
Melihat kondisi seperti ini, pihak pengelola universitas mengadakan perombakan. Setiap mahasiswa yang masuk harus melewati fase perpeloncoan terlebih dahulu. Untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak bangsawan itu agar tidak nakal, ugal, sombong dan patuh pada peraturan. Menurut sebagian orang, dari sinilah awal mula tradisi perpeloncoan itu.
Lalu kapankan tradisi ini masuk ke Indonesia? Data yang valid memang tidak ada, tapi tradisi ini berkembang di kampus-kampus Indonesia sekitar tahun 1950-an. Ketika itu, sudah muncul berbagai protes menentang perpeloncoan yang tidak manusiawi. Misalnya, nama Hutajulu dan kawan-kawan mencuat di kalangan mahasiswa�"kala itu�"saat memimpin aksi menentang perpeloncoan di Kampus UGM Yogyakarta. Gejala ini menunjukkan bahwa tidak hanya sekarang saja terdapat perpeloncoan di kampus. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa masalah lama kok sampai sekarang tidak kunjung usai?
Padahal, berdasarkan SK Menteri P&K No. 043/1971 Mapram (nama Ospek tempo dulu) telah dihapus. Tepatnya pasca kasus penyiraman soda api terhadap 19 dari 424 mahasiswa baru di ITS Surabaya. Peristiwa ini justru menunjukkan “kelemahan intelektual” bagi pengelola pendidikan di Indonesia.
Lantas, bagaimana bisa, kampus yang diimpikan sebagai tempat pergulatan wacana ilmiah, orientasi intelektual dan penggemblengan moral berubah menjadi ajang impulsi kekerasan?
Bukan kekerasan. Demikianlah dalih yang akan diberikan mahasiswa senior untuk menjawab sikap kritis mahasiswa baru yang memandang ospek adalah sebuah perbuatan bi-adab yang tak berprikemanusiaan.
Pada umumnya senior tidak ingin mahasiswa baru memiliki semangat juang yang rendah, karakter yang lemah serta kemampuan mempertahankan hak yang lembek. Setiap senior menginginkan mahasiswa baru memiliki semangat militansi sama seperti yang mereka (senior) miliki.
Lantas, untuk membentuk karakter mahasiswa yang kuat harus dibutuhkan apa? Penggemblengan militeristik? Perlakuan feodalistik? Atau bagaimana? Haruskan cara-cara kekerasan dalam menentukan sikap junior tetap diterapkan? Sementara, ribuan mahasiswa selalu berteriak anti pada kekerasan.
Apakah ini tidak terkesan berlebihan? Di satu sisi kita mendukung atas praktek-praktek kekerasan, sedang di pihak lain kita mengutukinya?
Satu yang penting untuk diingat, kegiatan ospek seperti sebuah pisau bermata dua. Sati sisi penting dilakukan, sisi lainnya banyak yang menginginkan kegiatan ini dihentikan. [hta]


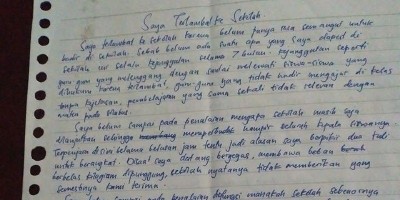












KOMENTAR ANDA